Cara Kaum Milenial Menjaga Nilai Budaya Aceh
Ada kalanya, mendefinisikan budaya menjadi sama rumitnya dengan memaparkan jawaban dari tanya tiba-tiba sang kekasih hati, "Mengapa sih kamu cinta aku?" Sebuah pertanyaan sederhana yang entah bagaimana bisa seketika mempercepat kinerja denyut nadi, mengacaukan ritme detak jantung, bahkan lebih buruk, menjadikan logika seketika lumpuh. Alih-alih menjawab dengan rangkaian kalimat puitis yang menghangatkan hati sang kekasih dari galau tanyanya, nahasnya, justru kita yang ikut-ikutan bengong, kemudian mempertanyakan ulang diam-diam dalam relung hati terdalam, "Memangnya mencintai butuh alasan ya?"
Demikianlah sekelumit skenario kacaunya pikiran saya, selaku kaum milenial, kala mencoba mendefinisikan, menilai, dan memahami ulang makna Nilai Budaya Aceh menurut versi kami. Sependek pemahaman, bagi saya pribadi, budaya itu laksana oksigen. Saya sadari kehadirannya. Saya gunakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan Saya yakini jika kelak ia lenyap, maka saya pun demikian. Namun jika ditanya, "Bagaimana membuktikan rupa oksigen itu?" Secara awam, saya akan kebingungan. Walau fakta saintifik menjamin penjelasannya dengan mudah.
Saya menduga, secara umum, masyarakat muda Aceh lebih familier dengan istilah budaya berkaitan dengan pegelaran seni, festival budaya, dan ragam kemegahan atraksi lainnya. Kesimpulan itu berdasarkan observasi via daring terhadap akun-akun sosial media para kerabat dan rekan sejawat generasi milenial. Saya pun berpendapat demikian dulunya.
Sadar akan terbatasnya kapasitas diri memahami tema budaya, saya pun melakukan diskusi lintas pikiran bersama para milenial lainnya. Seorang teman lulusan Ilmu Sosial dan Manajemen Konflik, Cici, memaparkan bahwa awal mulanya budaya hadir dari suatu hal atau kebiasaan yang terus menerus terjadi dalam suatu lingkup masyarakat. Katanya, "Kalau terjadi satu kali itu disebut kejadian, lebih dari tiga kali dinamakan kebiasaan. Nah, jika sering dan dilakukan terus menerus maka akan menjadi budaya."
 |
| Foto disadur dari film "Namaku Budaya" |
Saya pun mengangguk-angguk, paham. Pascatemu Cici, saya merasa tercerahkan. Tidak puas di situ, saya berinisiatif melanjutkan diskusi dengan teman milenial lainnya. Sasaran saya selanjutnya adalah tim film pendek, yang diprakarsai oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, berjudul "Namaku Budaya".
Keputusan ini berlandaskan kesan mendalam pascatonton film tersebut. Film berdurasi kurang dari setengah jam itu berhasil menggelitik jiwa saya dengan ragam rasa. Mulai dari pesona keindahan alam Gampong Lambaro Seubun, lucunya gelagat para pekerja di bengkel pembuatan rapai Pak Saad, kelezatan kue tradisional Aceh buatan Umi Halimah, ramahnya Dara dalam memuliakan tamu, hingga jenakanya sikap Budaya yang dipusingkan Tugas Akhir dan sang teman gaul, Banta, yang begitu penasaran dengan pegelaran Khanduri Blang di desa mereka.
 |
| Foto disadur dari film "Namaku Budaya" dan Ensiklopedia Budaya Aceh dan diedit |
Bak gayung bersambut, saya mendapat kesempatan mewawancarai Ponjria, aktor yang berperan sebagai Banta. Di sela kesibukannya, sebuah pertanyaan sederhana namun krusial terkait tujuan utama pembuatan film tersebut terlontarkan.
"Sebenarnya film 'Namaku Budaya' ingin mengabari masyarakat bahwa masih ada anak-anak muda yang peduli terhadap budaya," jelas Ponjria. Dia pun menambahkan, melalui film tersebut, para milenial dan anak-anak sekolah dapat terinspirasi membuat film-film lainnya yang juga mengandung nilai budaya.
"Sebenarnya film 'Namaku Budaya' ingin mengabari masyarakat bahwa masih ada anak-anak muda yang peduli terhadap budaya," jelas Ponjria. Dia pun menambahkan, melalui film tersebut, para milenial dan anak-anak sekolah dapat terinspirasi membuat film-film lainnya yang juga mengandung nilai budaya.
Sejatinya, saya turut mengamini niat tulus tersebut. Apalagi mengingat begitu pesatnya perkembangan dan peran teknologi di zaman modern ini, sehingga pendekatan karya-karya berbasis teknologi dan budaya Aceh menjadi hal urgen untuk terus diprioritaskan dan akan dibutuhkan untuk konsumsi positif generasi muda Aceh ke depan. Bagi saya pribadi, film yang dituliskan oleh Salman Varisi dan disutradarai oleh Tuanku Al-Absyar ini telah sukses memotivasi saya untuk semakin menyadari pentingnya merawat budaya Aceh sesuai perkembangan zamannya.
 |
| Foto disadur dari akun instagram Aceh Menonton |
Keluar dari dunia perfilman, saya pun melanjutkan observasi dan diskusi dengan rekan milenial lainnya. Target saya selanjutnya jatuh kepada perkumpulan anak muda Aceh penggemar musik HipHop and R&B yaitu Orang Hutan Squad (OHS) dan HipHop Nad Syndicate (HNS).
Alasan memilih mereka sederhana. Pertama, mereka adalah kumpulan dari generasi milenial. Kedua, saya jatuh cinta pada karya-karya mereka. Sejujurnya, dulu saya mengira HipHopers dan R&B Lovers (para pencinta dan pelaku musik bergenre HipHop dan R&B) adalah sekelompok seniman jalanan yang hobi rusuh dan ugal-ugalan. Setelah berkenalan dengan OHS dan HNS, secara tulus saya memohon maaf untuk stigma diskreditabel (tuduhan tanpa konfirmasi) untuk seluruh HipHopers dan R&B Lovers yang tetap menjunjung tata krama dan menghasilkan karya-karya luar biasa.
Sejatinya, perlakuan kita terhadap seseorang atau sekelompok golongan, walau baru dimulai dari pemikiran dan belum berwujud tindakan, itu semua merupakan bagian dari budaya. Oleh karenanya, selaku milenial Aceh, keteledoran semacam itu sama sekali tidak boleh saya ulangi lagi. Mengingat sikap mendiskreditkan orang lain bukanlah cerminan dari nilai-nilai Budaya Aceh yang seharusnya dipenuhi rasa kasih sayang dan kesetaraan nilai sebagai sesama makhluk Allah.
Alasan memilih mereka sederhana. Pertama, mereka adalah kumpulan dari generasi milenial. Kedua, saya jatuh cinta pada karya-karya mereka. Sejujurnya, dulu saya mengira HipHopers dan R&B Lovers (para pencinta dan pelaku musik bergenre HipHop dan R&B) adalah sekelompok seniman jalanan yang hobi rusuh dan ugal-ugalan. Setelah berkenalan dengan OHS dan HNS, secara tulus saya memohon maaf untuk stigma diskreditabel (tuduhan tanpa konfirmasi) untuk seluruh HipHopers dan R&B Lovers yang tetap menjunjung tata krama dan menghasilkan karya-karya luar biasa.
 |
| Foto disadur dari akun instagram OHS dan diedit |
Sejatinya, perlakuan kita terhadap seseorang atau sekelompok golongan, walau baru dimulai dari pemikiran dan belum berwujud tindakan, itu semua merupakan bagian dari budaya. Oleh karenanya, selaku milenial Aceh, keteledoran semacam itu sama sekali tidak boleh saya ulangi lagi. Mengingat sikap mendiskreditkan orang lain bukanlah cerminan dari nilai-nilai Budaya Aceh yang seharusnya dipenuhi rasa kasih sayang dan kesetaraan nilai sebagai sesama makhluk Allah.
Kembali ke diskusi bersama para musisi HipHop dan R&B. Melalui Marfa, sang Rapper OHS, saya memperoleh jawaban unik akan makna budaya. Tim OHS menyatakan bahwa mereka memandang budaya selayaknya bayi. "Budaya itu pada dasarnya diciptakan oleh manusia seiring berkembangnya zaman. Jadi, budaya pun berubah mengikuti zaman, selama tidak mengubah dasar kita sebagai seorang manusia."
Walau OHS dan HNS mempunyai visi dan karakter karya yang tidak serupa, para anak muda HipHop Nanggroe ini bersepakat untuk tetap memperkenalkan budaya leluhur kepada orang banyak melalui karya-karya mereka. Personil OH dari HNS, Andre Mandor, berpendapat, "Saya tidak lahir di masa budaya indatu (nenek moyang) diciptakan. Saya lahir dan berkembang di zaman sekarang sehingga tidak memahami secara mendetail budaya tersebut. Namun kemudian, kami mempelajari secara garis besar budaya leluhur, dan memperkenalkannya kepada dunia dengan cara kami."
Selaku sesama milenial, hati saya tak hanya terhenyuh karena karya mereka, namun juga sikap dan ketulusan mereka untuk tetap peduli menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya Aceh dengan cara kreatif ala kaum milenial. Oh iya, jika boleh curhat, lagu favorit saya dari OHS dan HNS adalah Hikayat Prang Sabi dan Piasan Raya. Saya bisa berulang kali mendengarkan kedua lagu tersebut. Apalagi kombinasi musik modern Hikayat Prang Sabi, karya Orang Hutan Squad, dipadu lirik dari ragam bahasa daerah di Provinsi Aceh. Sensasi mendengarkan lagu tersebut jadinya lebih menantang.
Saya sendiri juga turut berupaya menjaga nilai-nilai budaya Aceh di bidang Teknologi Informasi melalui pembuatan permainan edukasi Cempala. Tujuannya adalah mengajak masyarakat peduli proteksi alam dan satwa ikonis Aceh yakni burung Cempala (Cicem Pala). Mengingat kehadirannya menjadi unsur penggerak budaya cocok tanam, juga memengaruhi stabilitas ekonomi para petani pala di Aceh.
Demikianlah sekilas pengalaman saya dan kaum milenial dalam menilai dan menjaga budaya Aceh. Berikut tersedia pula Ensiklopedia Kebudayaan Aceh untuk para pembaca yang tertarik mempelajari budaya Aceh lebih mendalam. Sabah. []
Walau OHS dan HNS mempunyai visi dan karakter karya yang tidak serupa, para anak muda HipHop Nanggroe ini bersepakat untuk tetap memperkenalkan budaya leluhur kepada orang banyak melalui karya-karya mereka. Personil OH dari HNS, Andre Mandor, berpendapat, "Saya tidak lahir di masa budaya indatu (nenek moyang) diciptakan. Saya lahir dan berkembang di zaman sekarang sehingga tidak memahami secara mendetail budaya tersebut. Namun kemudian, kami mempelajari secara garis besar budaya leluhur, dan memperkenalkannya kepada dunia dengan cara kami."
Selaku sesama milenial, hati saya tak hanya terhenyuh karena karya mereka, namun juga sikap dan ketulusan mereka untuk tetap peduli menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya Aceh dengan cara kreatif ala kaum milenial. Oh iya, jika boleh curhat, lagu favorit saya dari OHS dan HNS adalah Hikayat Prang Sabi dan Piasan Raya. Saya bisa berulang kali mendengarkan kedua lagu tersebut. Apalagi kombinasi musik modern Hikayat Prang Sabi, karya Orang Hutan Squad, dipadu lirik dari ragam bahasa daerah di Provinsi Aceh. Sensasi mendengarkan lagu tersebut jadinya lebih menantang.
Saya sendiri juga turut berupaya menjaga nilai-nilai budaya Aceh di bidang Teknologi Informasi melalui pembuatan permainan edukasi Cempala. Tujuannya adalah mengajak masyarakat peduli proteksi alam dan satwa ikonis Aceh yakni burung Cempala (Cicem Pala). Mengingat kehadirannya menjadi unsur penggerak budaya cocok tanam, juga memengaruhi stabilitas ekonomi para petani pala di Aceh.
 |
| Foto disadur dari Ensiklopedia Budaya Aceh |
Demikianlah sekilas pengalaman saya dan kaum milenial dalam menilai dan menjaga budaya Aceh. Berikut tersedia pula Ensiklopedia Kebudayaan Aceh untuk para pembaca yang tertarik mempelajari budaya Aceh lebih mendalam. Sabah. []





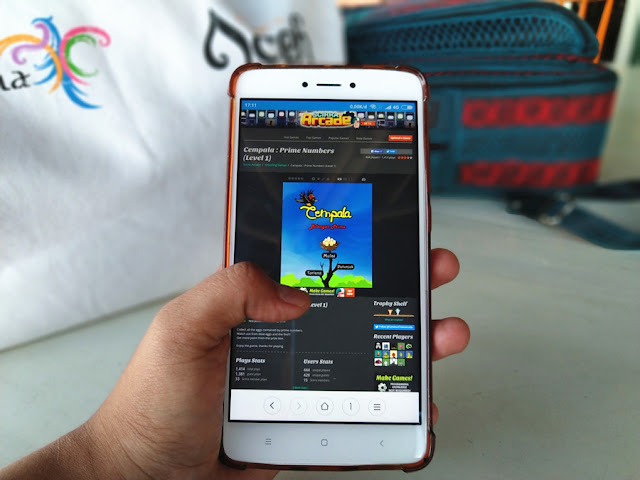
0 Response to "Cara Kaum Milenial Menjaga Nilai Budaya Aceh"
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya!
Besok-besok mampir lagi ya!
(Komentar Anda akan dikurasi terlebih dahulu oleh admin)